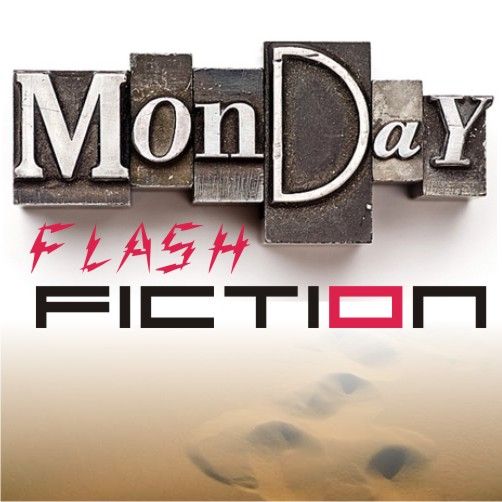Code Blue ~ International term for cardiopulmonary rescucitation, epinephrine and heart that didn’t stop praying.
***
Dua puluh empat jam pertama
Pantatku baru saja menyentuh kursi ketika pengeras suara di rumah sakit ini berteriak di segala penjuru.
“Code blue, ruang CVCU[1]. Code blue, ruang CVCU….”
Cardiac arrest[2].
Dengan terburu-buru, aku segera menuju CVCU. Seorang perawat sudah berinisiatif melakukan pijat jantung di dada Ny. Dariah, sedangkan seorang lagi memompa bag valve mask pada selang ETT[3] yang terjulur melalui bibirnya yang membiru. Aku melirik monitor. Garis naik turun tidak beraturan seperti hasil gambar balita yang baru bisa memegang pensil. Ventricular tachycardia[4].
“Sudah berapa lama?” tanyaku pada perawat yang sedang memompa ambubag. Kuraba leher Ny. Dariah. Tidak ada denyut di sana.
“Sekitar setengah menit, Dok.”
“Defibrilator[5] siap? 360 Joule!”
Kupegang gagang dua elektroda. “Clear[6]?”
Semua tenaga medis bersiap.
“Shock[7]!”
Tubuh Ny. Dariah melonjak karena kejutan listrik yang kutekan melalui paddle elektrode defibrilator di dadanya. Seorang perawat kembali menekan dada Ny. Dariah. Kulirik monitor. Tetap sama. Gambaran anak balita masih meliuk-liuk di layarnya.
“Epinefrin 1 mg!” instruksiku pada seorang perawat. Ia menyuntikkan cairan obat melalui selang infus, mengangkat tangan Ny. Dariah selama beberapa detik, lalu meletakkannya kembali.
Seorang perawat pria berdiri di atas pijakan kaki, lalu melakukan pijatan di atas dada Ny. Dariah. Kutatap nanar perempuan tua tak berdaya di hadapanku. Acute myocardial re-infarction on posterior – inferior – lateral[8]. Reinfarction. Serangan jantung yang berulang.
Aku teringat cerita rekan sejawat, betapa Ny. Dariah adalah pasien dengan semangat juang tinggi. Ia telah mengalami henti jantung setidaknya empat kali, termasuk malam ini. Namun Tuhan masih belum berkenan memanggilnya pulang. Kata orang, sepertinya beliau sedang menunggu. Entah apa. Atau siapa.
Kuambil dua gagang paddle elektrode dan bersiap melakukan kejut jantung untuk yang kedua kali. Dalam hati aku berdoa, semoga Ny. Dariah tidak meninggal malam ini. Setidaknya, tunggulah hingga seluruh keluarganya ikhlas melepaskan. Setidaknya, tunggulah hingga rasa rindunya pada dunia fana terpenuhi. Setidaknya, tunggulah hingga tugas jagaku berakhir.
“360 Joule! Clear? Shock!”
***
Dua puluh empat jam kedua
Code Blue. Sebuah istilah internasional terhadap sebuah kondisi di mana jantung dan/atau paru mulai berhenti berfungsi. Entah mengapa disebut biru. Karena bagiku, biru adalah simbol yang dinamis. Bahkan untuk beberapa lelaki, biru dekat dengan hal-hal yang tidak baik. Film biru, misalnya.
Atau mungkin, biru yang dimaksud adalah arti biru bagi perempuan. Kesedihan. Rasa takut akan kehilangan, yang menggantung pada ujung-ujung jari dan bibir yang membiru ketika darah dan oksigen tak lagi dialirkan karena jantung dan paru berhenti memberi makan.
Ah.
Aku sudah lupa kapan terakhir makan layak dan cukup beristirahat. Kepalaku terasa kosong. Badanku melayang. Bahkan perutku sudah lupa rasanya lapar. Jika seorang dokter berkata pada pasien-pasiennya, “Makan teratur dan cukup tidur,” maka percaya saja agar tidak berubah menjadi zombie berjalan. Seperti aku.
Tiba-tiba aku teringat. Lebaran lalu, seorang kawan lama menghubungiku. Teman-teman SMA akan mengadakan reuni. Tentu saja, aku tidak bisa hadir. Bagi dokter umum, hari libur adalah mimpi buruk. Akan selalu ada perebutan jadwal jaga demi kata libur. Dan meskipun akhirnya bisa libur, biasanya tidak pas pada harinya. Pada akhirnya, liburan dihabiskan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Nonton TV, baca koran, atau tidur seharian.
Mengetahui jadwal jagaku yang seperti kerja rodi, salah seorang teman berkomentar, “Jangan kerja terus. Bersenang-senanglah sedikit.”
“Lalu siapa yang mau menanggung uang sekolah anak sulungku bulan depan?”
Tapi jawaban itu kusimpan dalam hati saja. Di dunia ini, siapa yang bisa percaya bahwa seorang dokter bisa mengalami kesulitan keuangan?
Aku mengurut kakiku yang mulai bengkak. Berdiri, berjalan, berlari di lorong-lorong rumah sakit selama belasan jam membuat kedua kakiku meronta kelelahan. Di saat-saat seperti ini, aku sering membayangkan enaknya bekerja di balik meja. Mengetik atau merancang sesuatu yang berguna. Berargumen tentang naiknya harga saham, atau bagaimana menembus pasar dunia dengan produk-produk baru yang istimewa. Serta menikmati hari libur seperti orang-orang pada umumnya.
Ah, tapi hidup itu sawang sinawang[9], bukan? Ketika aku berpikir demikian, ada banyak orang yang berlomba-lomba meninggikan tawaran uang untuk memasukkan anak-anak mereka ke fakultas kedokteran. Sebuah fakultas yang bagiku dulu adalah tempat untuk mengubah nasib. Rakyat jelata, anak buruh pabrik dengan penghasilan tak seberapa, nekat bersaing dengan ribuan hati yang tertambat pada satu profesi yang dianggap mulia dan menyejahterakan.
Namun bayangan hidup sejahtera itu pudar saat titel dokter sudah resmi kusandang. Ketika rekan-rekan seusiaku sudah mampu mandiri dengan satu rumah dan beberapa kendaraan, aku hanya mampu membayar rumah kontrakan. Satu juta sekian per bulan, tidak ada lagi yang tersisa untuk ditabung atau mencicil rumah sendiri. Apalagi mobil.
Dan untuk menambah nominal itu, aku harus bekerja seperti orang kesurupan. Beralih dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Berjalan di lorong yang dingin dan sepi bagai orang gila. Karena tidak hanya istri dan anak yang kupunya. Tapi ibu dan dua adik yang masih kuliah juga menjadi tanggunganku.
“Permisi, Dok. Ada keluarga Bu Dariah yang mau ketemu dr. Aulia.”
Suara Bu Sum – kepala bagian kebersihan – mengagetkanku. Aku mengangkat kepala yang hampir terjatuh dan tertidur di atas meja ruang jaga. Menggosok-gosok mata dan tersenyum sumringah. “Makasih, Bu Sum. Sebentar lagi saya ke CVCU.”
Kucuci muka sekadarnya. Jam sebelas lewat sepuluh menit. Empat puluh jam sudah aku di rumah sakit ini. Tanpa mampu beristirahat sama sekali.
“Terima kasih sudah menyelamatkan Ibu. Ini sudah keempat kalinya beliau mengalami henti jantung. Rasanya, jantung saya seperti mau lepas setiap perawat dan dokter masuk terburu-buru ke CVCU,” ujar seorang wanita berjilbab yang kuduga usianya sepantaran denganku.
Aku tersenyum mendengarnya. Wajar saja. Karena aku pun merasakan hal yang sama. Jantung, paru, otak. Semua terasa ingin melesat keluar tubuh setiap panggilan ‘Code Blue’ dikumandangkan. Jika keluarga pasien merasa berduka karena kondisi buruk keluarganya, maka paramedis mati berkali-kali setiap ada pasien yang kondisinya semakin turun dan sulit disembuhkan.
“Sama-sama. Keluarga banyak berdoa, ya. Karena kami hanya mampu mengusahakan apa yang bisa dikerjakan manusia. Hidup atau mati itu apa kata Tuhan,” ujarku.
Wanita itu tersenyum. Begitu juga aku. Merasa bahagia telah bisa menyelamatkan beberapa hati keluarga Ny. Dariah dari kedukaan. Lega, setidaknya kasus kematian tidak bertambah. Karena jika itu terjadi, aku tidak tahu apa yang akan membayangi. Karena ketakutan atas tuduhan malapraktik semakin gencar sekarang. Menjadi dokter tidak lagi leluasa menerapkan seni pengobatannya.
Namun kebanggaanku atas penyelamatan Ny. Dariah yang heroik tadi tidak bertahan lama. Aku disergap kalut setelah membaca sebuah pesan dari istriku yang baru saja kuterima.
From: Astrid
Mas, badan Arga tiba-tiba dingin. Tidur terus, enggak mau dibangunin. Mimisan juga. Gimana?
Received: 16 November 2013; 23:47 WIB
Senyum yang tadi mengembang sempurna harus kutelan lagi.
For: Astrid
Bawa ke sini sekarang. Naik taksi saja.
Sent: 16 November 2013; 23:56 WIB
Empat puluh jam lebih aku menjagai pasien-pasien di sini, namun aku bahkan tak mampu memeluk kesakitan anakku sendiri.
***
17 November 2013; 00:34 WIB
Dengan setengah berlari, aku bergegas ke unit gawat darurat. Istriku baru saja menelepon, Arga mengalami demam berdarah pre-syok. Jantungku berdentam tak karuan. Mengapa sampai tidak ketahuan? Mengapa Astrid sama sekali tidak lapor padaku? Mengapa?
Segala pertanyaan, kekesalan, amarah dan rasa kecewa karena telah menjadi ayah yang gagal berkecamuk di dadaku. Namun semuanya buyar ketika…
“Code blue, lantai dua, ruang ICU[10]. Code blue, lantai dua, ruang ICU….”
Sial! Mengapa harus di saat-saat seperti ini?
Aku terdiam selama beberapa saat. Ponselku berdering tanpa henti. Astrid dan Arga membutuhkanku. Dan pasien ICU itu juga menungguku. Aku bisa membayangkan wajah Arga yang pucat. Namun sekelebatan wajah pasien ICU yang membiru itu menari-nari di pelupuk mata.
Dadaku sesak. Menahan keputusan yang sama sekali sulit. Selalu ada yang harus dikorbankan. Selalu ada.
***
17 November 2013; 00:35 WIB
Dengan tergesa-gesa aku menuju ICU. Beberapa detik kemudian, aku telah berada di samping seorang lelaki tua. Seorang pasien 75 tahun dengan gagal napas karena penyakit obstruktif baru kronis yang ranjangnya terletak paling ujung ICU. Mulutnya menganga. Tubuhnya diam saja. Dan biru di bibirnya.
Monitor jantung menunjukkan garis lurus saja. Tidak naik. Tidak turun. Lurus. Seperti hidupku yang hanya tahu jalan antara rumah dan rumah sakit. Tidak pernah belok ke mana-mana.
“Asystole[11] sudah berapa lama?” tanyaku.
Kubuang selimut bergaris-garis biru agar tampak jelas dada kakek tua itu. Tidak ada gerakan dada atau tanda-tanda bahwa tubuhnya masih bekerja. Kutempelkan ujung jari ke bagian belakang lehernya. Tidak ada denyutan.
“Semenit, Dok!” jawab salah seorang perawat pria.
Aku naik ke sebuah pijakan dan segera memimpin CPR – cardiopulmonary rescucitation. Perawat itu melepas tube yang menghubungkan ETT pada ventilator, lalu menggantinya dengan bag valve mask.
“Epinefrin 1 mg!”
Obat kehidupan itu disuntikkan.
Satu, dua, tiga, empat, lima, …
Arga juga sekarat. Sama sepertimu, Bapak tua.
enam, tujuh, delapan, sembilan, …
Tapi aku memilih menyelamatkanmu daripada menenangkan anak sulungku.
sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, …
Padahal aku tahu, kamu terbaring dan hampir mati seperti ini karena ulahmu sendiri. Rokok empat bungkus sehari?
enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, …
Ponselku berdering lagi.
Ya Tuhan, aku telah bersalah karena menelantarkan istri dan anakku. Jika memang keluarga lebih penting daripada uang, lalu bagaimana caraku mengisi pundi-pundi tabungan untuk istri, anak-anak, ibu, dan juga adik-adikku tanpa dibatasi tenaga dan waktu?
dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, …
Keparat. Cepatlah. Cepat kembali atau tidak sama sekali. Aku harus segera pergi dari sini!
dua puluh enam, dua puluh tujuh, dua puluh delapan, dua puluh sembilan, …
tiga puluh.
Tiga puluh tekanan pada dada. Entah sudah siklus keberapa. Lima belas menit berlalu sejak kulakukan CPR pertama. Atropin dan epinefrin telah diberikan secara bergantian. Kutempelkan lagi jariku di atas arteri karotis. Tidak ada denyutan. Garis lurus di monitor juga tetap tidak mau berubah.
Aku dan perawat ICU berpandangan. Aku tahu, kami semua merasakan hal yang sama. Sebuah perasaan campur aduk yang tidak bisa dideskripsikan. Antara lelah, marah, sedih, dan kecewa atas kegagalan.
“Panggil keluarganya,” seruku lirih. Memandangi seorang perawat melepas selang dan alat ventilator dari tubuh kakek tua. Lalu menutup wajahnya dengan selimut bergaris-garis biru yang tadi sempat kubuang.
Ah, Pak Tua. Maafkan aku yang tidak mampu mengembalikan napas dan denyut jantungmu. Sepertinya ini memang sudah waktumu untuk pulang. Dan aku harus segera menemani anakku yang malang.
“Tn. Sartono, 75 tahun. Meninggal tanggal 16 November 2013 jam 00:51 WIB.”
Ponselku bergetar pelan. Ada sebuah pesan.
From: Astrid
Mas, Arga sudah dalam kondisi syok. Harus masuk PICU[12].
Received: 17 November 2013; 00:52 WIB
Tubuhku lunglai. Ada beban berat yang rasanya tak mampu kutanggung. Dengan langkah terseret, aku berusaha keluar dari ICU. Karena aku tidak mau orang-orang tahu kedukaanku.
Tuhan, tolong ambil sakit Arga, dan pindahkan saja semuanya padaku.
Kutelurusi daftar nama di ponsel. Meminta bantuan teman sejawat untuk menggantikanku jaga. Setidaknya sampai Arga sembuh total.
Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Seharusnya sudah seminggu yang lalu. Namun sampai saat ini aku belum mengirim uang untuk Ibu dan adik-adikku. Dan kekesalanku bertambah pilu. Saat mendapati tiket seminar yang setara dengan gaji sebulan di sela-sela dompetku.
Tidak kerja berarti tidak dapat penghasilan.
Almarhum Bapak selalu bilang. Jadilah dokter yang bermartabat. Penuh pengabdian dan rasa ikhlas.
Aku selalu demikian, Pak. Kuabdikan ilmuku demi pasien-pasien ini. Namun sekarang aku menyadari sesuatu. Idealisme tidak mampu menghidupiku, anak dan istriku, Ibu dan adik-adik yang kau tinggalkan untukku.
***
Code blue. Code blue. Code blue.
Kali ini bukan pengeras suara rumah sakit yang bertalu-talu. Itu mata hatiku, sekarat dan membiru. Digantikan oleh mata yang melebar di telapak tangan ketika ia mulai menggoreskan tanda tangan di atas kontrak yang disodorkan pabrik obat dua bulan yang lalu.
***
Malang, 21 November 2013
Catatan Kaki:
[1] Cardiovascular Care Unit: Unit khusus bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah.
[2] Henti jantung.
[3] Endotrachel tube: tabung yang digunakan untuk membuka jalan napas dari mulut hingga trakea.
[4] Jantung memompa secara abnormal karena titik sinaps listrik jantung yang berubah.
[5] Stimulator detak jantung yang menggunakan listrik dengan tegangan tinggi untuk memulihkan serangan jantung.
[6] Instruksi agar semua orang di sekitar pasien tidak menyentuh pasien atau alat-alat yang terhubung dengan tubuh pasien, termasuk ranjang pasien.
[7] Peringatan bahwa listrik sedang dikejutkan.
[8] Infark miokard akut (serangan jantung karena sumbatan pada pembuluh darah) pada pembuluh darah bagian belakang, bawah dan samping
[9] Pepatah Jawa, artinya hidup itu tergantung dari cara dan sudut pandangnya..
[10] Intensive Care Unit
[11] Garis datar pada elektrokardiograf.
[12] Pediatric Intensive Care Unit: ruang perawatan khusus untuk anak-anak dengan kondisi kritis.
PS: Pernah dimuat di #RainbowProject berjudul Blue(s)