Sonata No. 2 In B Flat Minor
Tidak ada yang lebih menyayat dari perpaduan hujan lebat di siang hari, pilihan sulit dan lagu patah hati. Di bawah sinar mentari yang membakar kulit, engkau justru merasakan dinginnya air hujan yang melumat habis hangatmu. Belum lagi dilema antara pilihan-pilihan yang semuanya bisa membunuh masa depan. Atau masa lalu. Dan alunan nada pedih yang membuatmu ingin mengiris nadi. Saat itu juga.
Itulah yang kurasakan siang ini. Hujan lebat di luar sana. Begitu hebat hingga aku tidak bisa pergi ke mana-mana. Sepuluh menit yang lalu, sebuah pesan kuterima. Pesan singkat. Pesan yang membolak-balik duniaku. Dan entah kenapa, playlist di laptop kerjaku memutar lagu Separated milik Usher. Keparat.
Dua setengah jam lagi, ada rapat penting yang harus kupimpin sendiri. Tidak dapat diwakilkan. Tetapi pesan singkat tadi juga tidak bisa kutangani melalui orang lain. Harus aku sendiri. Dilema. Hujan. Dan lagu patah hati.
“Vaya, kamu tenang dulu. Kita ketemuan di tempat biasa. Setengah jam lagi aku sampai di sana. Percayalah. Semua akan baik-baik saja.”
Aku menutup telepon. Berusaha untuk terdengar tenang di saat gemuruh mencabik-cabik hati, sungguh tidak menyenangkan. Tapi kurasa, pilihan kata dan suaraku tadi sudah cukup meyakinkan Vaya, bahwa semua akan baik-baik saja. Iya, semoga saja begitu. Karena aku sendiri pasti akan ragu jika mendengar saran atau nasehat yang ragu-ragu.
Aku sampai pelataran di Resto Classic sepuluh menit lebih awal. Kuparkir mobilku dengan serampangan. Otakku sudah tidak mampu berpikir secara benar. Langkah kakiku sudah tidak karuan. Berpacu dengan detak jantung yang berdentuman. Lup dup lup dup lup lup dup dup lup lup lup dup dup dup.
Rupanya Vaya sudah tiba. Wajahnya pucat. Bibirnya saling berpagut. Biasanya, melihat bibirnya sudah membuatku hilang akal. Tetapi siang ini, aku tidak mau akalku hilang.
“Mas… Gimana ini?” kata Vaya saat aku mendekati mejanya. Dia bahkan berdiri dari duduknya. Dan tidak bisa menyembunyikan kegelisahan.
“Kita bicarakan semuanya siang ini. Kamu sudah makan?” kataku. Sambil mengelus pelan lengannya yang gemetar. Lalu menuntunnya duduk bersamaku. Berdampingan.
“Aku ndak nafsu makan,” ujarnya sambil menggeleng dan hampir menangis.
Gawat. Aku tidak pernah suka perempuan yang menangis. Apalagi di tempat umum seperti ini. Rasanya seperti penjahat asmara yang tega membuat seorang hawa sakit hati.
Aku mengedarkan pandang dan bernapas lega. Sepi. Tidak ada pengunjung lain. Jadi aku tidak harus berpura-pura larut dalam drama siang ini.
“Oke. Aku pesankan makanan dulu ya. Kamu harus makan. Setelah itu, baru kita bicara.”
Aku bangkit dan menuju meja pemesanan. Menyebutkan dua porsi makan siang. Jemariku mengetuk-ngetuk tidak sabar. Rasanya ingin segera kuselesaikan. Tetapi tidak bisa. Harus perlahan. Tuhan tidak suka hamba yang terburu-buru. Karena akupun tidak mau, dilema ini berakhir dengan pilu.
Aku kembali ke tempat duduk kami dengan membawa satu nampan berisi makanan untuk berdua. Kemudian kami menikmati makan siang dalam diam. Sesekali kuseka bekas saus di ujung bibirnya. Cantik sekali. Perempuanku itu cantik sekali siang ini.
“Jadi… masalah ini bagaimana, Mas?” tanya Vaya. Tepat setelah suapan terakhirnya. Ia menyodorkan sebuah foto hitam putih. Cukup buram, tetapi aku tahu gambar apa yang ada di sana.
“Aku tidak mengira bahwa ini akan terjadi, Sayang. Ternyata metode kalender kita tidak tepat,” jawabku sambil menyeka mulut dengan selembar tisu. Tanganku meraih foto hitam putih itu. Bagaimanapun aku penasaran, sebesar apa janin yang ada di rahim Vaya. Ada tonjolan sebesar 5 mm, gestational sac, 4 – 6 minggu.
“Aku juga nggak. Trus aku harus gimana?” Vaya mulai panik. Sebagian dari diriku merasa, perilaku Vaya ini cukup menggelikan. Biasanya, kehamilan justru digunakan perempuan untuk mengancam laki-laki agar segera menikahinya. Tetapi tidak dengan Vaya.
“Kalo… digugurkan bagaimana?” tawarku. Hati-hati sekali. Perempuan hamil biasanya memiliki naluri keibuan yang kuat. Naluri ingin melindungi. Atau malah menjelma sebagai monster pembunuh janin karena tidak ingin kehamilan menghambat hidupnya.
“Nggak! Aku nggak mau aborsi!”
Nah. Rupanya Vaya termasuk perempuan yang pertama. Baiklah. Aku akan membuatnya semakin mudah.
“Aku akan cari cara, Sayang. Seperti yang kamu tahu, sudah lama aku ingin menceraikan istriku. Bahkan sebelum bertemu denganmu. Jika seperti ini keadaannya…”
“Cari jalan keluar! Aku nggak mau anak ini lahir sebagai anak haram!” Dan air mata Vaya tumpah sudah. Aku mencoba menenangkannya dengan memberi belaian lembut di tangannya yang basah oleh keringat.
Inilah alasannya, aku memilih Vaya sebagai selingkuhan. Terlalu polos, lugu, kadang-kadang bodoh. Jika tidak mau punya anak haram, kenapa mau diajak berhubungan haram, Vaya…
“Masalah seperti ini tidak bisa aku putuskan dengan tergesa-gesa, Sayang. Tapi yakin, aku pasti bertanggung jawab. Kamu jangan terlalu gelisah memikirkan hal ini. Kamu calon ibu. Harus kuat ya…”
Kalimat yang kuhapal sepanjang jalan tadi akhirnya keluar juga. Aku melihat, Vaya tersenyum ringan. Tawa kecilnya mulai terdengar. Dan dadaku melonggar. Menyelesaikan masalah ini dengan Vaya ternyata tidak butuh usaha banyak.
Kupeluk tubuhnya yang rapuh. Kukecup bibirnya yang basah. Aroma parfum dan rasa bibir Vaya tidak pernah berubah. Seperti sedang mengulum gula-gula rasa strawberry yang manis, dan wanginya mendesak seluruh sistem untuk meminta lebih. Aku tertawa dalam hati. Sialan. Semua dilema ini ada gara-gara aroma dan rasa strawberry. Dan mulai detik ini, aku membenci strawberry.
“Mainkan sebuah lagu, Mas,” pinta Vaya. Matanya melirik sebuah piano mewah.
“Kamu mau denger lagu apa?” tanyaku.
Vaya mendekatkan lagi tubuhnya ke arahku, “Apa saja. Dari Chopin. Lagu-lagunya selalu membangkitkan sisi romantisme bagi siapapun yang mendengarkan. Ekspresif dan penuh hasrat. Seperti rasaku buat kamu.”
Aku tersenyum mendengar permintaannya. Kugenggam kedua tangannya. Lalu beranjak, dan berjalan menuju piano hitam di tengah ruangan.
Dentingan piano menggema di restoran yang kosong ini. Nadanya jernih dan begitu intim. Senada dengan dentuman hujan di luar sana, mengiringi irama hatiku dan Vaya. Mengingatkan pada saat kami terbakar dan bercinta. Sesekali aku melempar senyum ke arah Vaya yang tampak lebih tenang. Dia membalas senyumanku, lalu meneguk habis jus tomat yang kupesankan. Hati berbunga melihatnya.
Tiba-tiba Vaya memegangi lehernya. Napasnya memendek. Dan cepat. Suaranya parau memanggil-manggil namaku. Kumainkan lagu ini dengan tempo lebih cepat. Berlomba dengan waktu yang tak lagi lama.
Tubuh Vaya mengejang. Matanya terbelalak begitu mengerikan. Lalu ia terjatuh ke lantai. Dan menggeliat-geliat seperti lintah yang disiram garam.
Baiklah. Inilah puncaknya. Tempo permainan pianoku makin menggila. Dentingan piano tidak lagi bisa didefinisikan. Hanya terdengar alunan lagu kematian yang memburu dan menderu seperti pusaran angin yang marah. Ini seperti lomba lari yang harus aku menangkan.
Tubuh Vaya melemas perlahan. Buih putih keluar dari mulutnya. Kemudian gerakan tubuhnya sirna. Dengan mata yang masih memintaku untuk memandangnya.
Vaya… Tadinya aku bangga mendengarmu menyebutkan tentang Chopin dan lagu-lagunya. Tetapi sepertinya kamu tidak tahu. Bahwa lagu yang kumainkan ini, Sonata no. 2 in B Flat Minor, adalah lagu pengiring kematian Chopin setelah dilanda patah hati. Sepuluh tahun ia merelakan cintanya hanya dihargai nomor dua. Dan Goerge Sand meninggalkan Chopin demi suami sahnya. Lalu sakit dan merana. Hingga nyawanya tiada. Seperti kamu, Vaya. Seperti kamu, yang kutinggalkan demi istri sahku.
Jariku menari tanpa jeda. Dan dua menit setelah Vaya tiada, aku mengakhiri resital tunggalku. Perfecto. Napasku melambat. Denyut jantungku tak lagi cepat. Kupejamkan mata dan menikmati harmoni yang baru saja kumainkan. Simfoni piano, hujan dan lagu kematian memang begitu sempurna.
***
Moru – Alor – NTT
December 11th 2012


















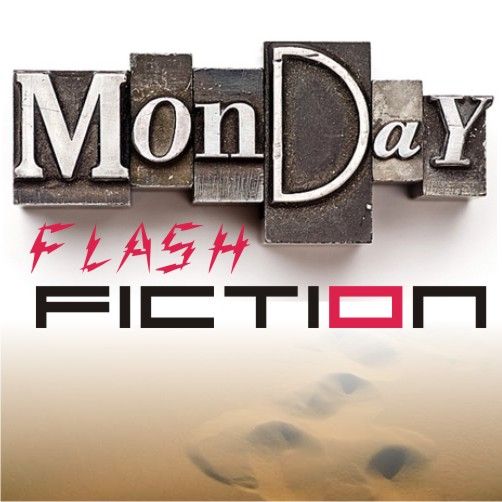


keren …
Terima kasih sudah mampir ^^
iki apik… #tsaaah
Tengkyuuu… :’)
harusnya ada cue and clue,,
trus PDx, PTx, dan PMx,,
*MR IPD be’e*
hehehe,,
Contoh cue and cluenya apaaah? *Ngeblank*